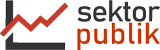Bagi beberapa golongan, menjadi partai pemerintah berarti juga “membagi rezeki”. Golongan sendiri diutamakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri ditugaskan partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang menteri perekonomian, misalnya, menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan memberikan lisensi dengan bayaran tertentu untuk dia setorkan ke kas partainya.
Kutipan di awal merupakan sebagian kalimat yang dicuplik dari tulisan Mohammad Hatta dalam buku Demokrasi Kita. Hatta menulisnya sebagai bentuk kegelisahan betapa jabatan menteri menghadapi dilema di satu sisi harus menjadi negarawan berintegritas. Di sisi lain ada godaan rente yang salah satu berasal dari partai pengusung pemerintahan.
Refleksi ini jadi relevan pada setiap transisi kepemimpinan nasional kontemporer, di mana presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memilih para menteri menjalankan pemerintahan 2024-2029. Maka bolehlah warga negara – tak hanya konstituen – berharap Presiden akan menggunakan hak prerogatifnya dengan sebaik-baiknya. Ini berarti menjadikan kompetensi dan integritas sebagai kriteria utama di atas kepentingan golongan, sehingga kabinet berisi para negarawan handal. Dalam hal kriteria kompetensi ini, istilah kabinet zaken sering dikutip. Belakangan Prabowo Subianto berencana mengusung konsep ini untuk kabinet koalisi Indonesia Maju periode 2024-2029. Istilah kabinet zaken yang dimaksud ialah jajaran menteri yang sebagian atau seluruhnya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
Dalam sejarah Indonesia, sebutan kabinet zaken yang diterjemahkan sebagai Kabinet Karya pernah diusung pada masa Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada periode 1957 sampai dengan 1959. Selain Djuanda yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan, dari 23 posisi menteri lainnya ada 10 yang tidak dijabat yang tidak berafliasi ke partai politik. Sisanya merupakan kader NU, SKI, Masyumi, Parkindo, PNI, dan PSII. Maka ini menjelaskan pun dalam suatu susunan yang diharapkan benar-benar kompeten, tetap diperlukan dukungan politik dari parlemen untuk menjamin kestabilan politik.
Jumlah menteri yang pada masa kabinet parlementer masih pada kisaran 20an, lalu melonjak menjadi lebih dari seratus posisi pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Jika ditilik, pada masa ini mulai muncul berbagai urusan yang dipecah. Contohnya Menteri Perindustrian Tekstil, Menteri Perindustrian Ringan, Menteri Pengairan Dasar, Menteri Pengairan Rakyat, yang pada masa kepemimpinan Presiden Suharto dilebur ke dalam klaster kementerian terkait. Selain dihuni para veteran menteri lintas partai politik, Kabinet Dwikora diisi oleh 32 perwira militer. Hal ini mencerminkan keinginan Presiden Sukarno juga untuk menjadikan posisi para menteri sebagai alat mengelola dukungan politik khususnya dari militer ketiga matra dan kepolisian.
Pada masa awal Orde Baru di tahun 1968, Presiden Suharto mengelola Kabinet Pembangunan I yaitu para menteri yang jumlahnya tetap ramping, tak sampai 30. Jumlah ini kemudian berubah mendekati 40 jabatan seiring peleburan di satu sisi dan pemekaran fungsi di sisi lain. Peleburan misalnya seluruh matra militer dan kepolisian berada di bawah komando Panglima ABRI. Pemekaran di antaranya adanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang awalnya bergabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan. Juga, mulai munculnya jabatan menteri senior atau Menteri Koordinator yang membantu Presiden mengelola rumpun kementerian tertentu. Jika di awal Presiden Suharto masih melibatkan satu orang dengan latar belakang partai politik selain mulai terlibatnya para teknokrat, Golongan Karya dan militer, di periode berikutnya dia semakin menggunakan hak prerogatifnya seiring semakin menguatnya kabinet presidensial. Selain hegemoni kekuasaan tiga pilar – ABRI, Birokrasi, dan Golkar – ada fusi pada tahun 1973 sehingga jumlah partai politik berkurang drastis dari sepuluh menjadi tiga.
Kabinet Presidensial dan Kepartaian
Pasca Orde Baru – periode yang sering disebut Masa Reformasi – justru dalam 20 tahun terakhir menimbulkan ketidakstabilan, di mana para Presiden harus berakrobat menghadapi hiruk pikuk aspirasi partai-partai politik pendukung. Hal ini dibayar sangat mahal dengan sejumlah menteri dari partai pendukung tersangkut pidana korupsi yang diusut Kejaksaan dan KPK.
Penyederhanaan partai politik di masa Orde Baru berpijak pada pembelajaran pemerintahan yang stabil perlu lebih bisa mengelola hiruk pikuk aspirasi politik. Dalam khazanah pengetahuan, ini sesuai gagasan ilmuwan politik Juan José Linz dan Scott Mainwaring bahwa kombinasi multipartai dan presidensial penyebab situasi tidak stabil. Linz dan Mainwaring juga merujuk Chili dan Brazil. Dalam kasus Chili, Linz merujuk krisis politik di tahun 1970an di mana Presiden Salvandor Allende tidak memiliki dukungan mayoritas parlemen, sehingga mengalami kebuntuan. Hal yang sama juga dialami Brazil di tahun 1960an.
Belakangan tesis Linz dan Mainwaring ditelisik José Antonio Cheibub bahwa pilihan presidensial atau parlementer dan jumlah partai sejatinya tidak terkait dengan stabilitas. Dalam konteks Indonesia dan sejumlah negara di Amerika Latin, negara yang mengalami transisi demokrasi dari rezim otoriter mewarisi lembaga-lembaga yang lemah, konflik politik yang belum diselesaikan, dan polarisasi yang rumit. Dalam hal kepartaian, masalah muncul bukan karena banyaknya partai, namun bagaimana masing-masing partai diorganisasi dan bagaimana relasi antara legislatif dan presiden dikelola.
Cheibub menggarisbawahi sistem presidensial sudah punya mekanisme dalam menyelesaikan konflik. Tak hanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur yang memberi ruang sirkulasi elit, namun juga kebuntuan yang sering terjadi dapat diselesaikan melalui negosiasi politik.
Dalam kasus Indonesia kontemporer, bentuk riil negosiasi dilakukan dengan membangun aliansi dengan sebanyak-banyaknya partai politik sehingga setiap usulan peraturan dan kebijakan dapat dijalankan. Selain konsekuensi perburuan rente, juga muncul campur tangan terhadap kelembagaan negara – contohnya MK, MA dan KPK – sebagai bagian dari akrobat politik kekuasaan. Hal ini justru menunjukkan blunder dalam kompetensi tidak hanya kementerian namun juga lembaga penegak hukum. Dengan wajah dan pola aliansi politik presiden terpilih yang sama dengan periode sebelumnya, maka wajar jika publik menganggap rencana membentuk kabinet zaken yang lebih profesional hanya menjadi gimik. Apalagi kompetensi yang menjadi syarat utama dalam model kabinet ini justru tercederai justru dengan posisi wakil presiden terpilih sebagai hasil campur tangan terhadap MK.
Kabinet Negarawan, Mungkinkah?
Jika ada pertanyaan, ‘apakah masih memungkinkan pada periode ini ada suatu kabinet yang diisi para negarawan handal di bidangnya?’ Sejauh ini dapat dijawab masih jauh panggang dari api. Konsolidasi kekuatan politik sangat memungkinkan akan merubah konfigurasi aliansi dan tentunya bakal berimbas terhadap figur dan jumlah jabatan menteri.
Maka harapan berikutnya ada pada Prabowo sebagai presiden terpilih. Pertama, presiden nantinya diharapkan berkepentingan untuk melakukan perbaikan radikal di masa depan. Dimulai dengan melakukan suatu asesmen kapabilitas nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan kementerian yang sesuai untuk Indonesia. Sekaligus merumuskan struktur yang efektif bagi pencapaian Visi Indonesia Emas di tahun 2045 dan secara mikro sesuai dengan penjuru capaian per lima tahun. Tentunya termasuk bagaimana mengelola relasi dengan partai politik pendukung dan DPR, serta mau meninggalkan cara-cara campur tangan yang merusak kelembagaan negara.
Di sisi lain, sebagai bagian dari hak untuk berperan serta, publik yang merasa berkepentingan bekerja sama dengan perguruan tinggi dapat melakukan asesmen sebagai bahan advokasi. Pada periode akhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, asesmen yang dimaksud sebetulnya sudah pernah dilakukan sebagai bagian dari inisiatif awal Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Namun dokumen tersebut masih perlu penyempurnaan sampai ke level eselon 1 dan 2. Beberapa hasil, di antaranya rumpun PAN, BKN, LAN dan BPKP seharusnya dilebur menjadi satu badan. Dengan dinamika RBN yang menghadapi kendala internal berbentuk penolakan di masing-masing kementerian, maka penulis menilai bahwa badan yang dimaksud seharusnya berada sebagai bagian lembaga Kepresidenan. Hal ini untuk memberi kekuatan penuh bagi setiap inisiatif perubahan kelembagaan.
Kedua, Presiden sebagai kepala negara perlu mulai mendorong dan merumuskan kebijakan serta tindakan agar partai politik dapat lebih berintegritas, akuntabel, dan berdisiplin. Sebagai hulu dari berbagai kebijakan, maka kontradiksi berbagai prinsip tata kelola pemerintahan seharusnya tidak diperkenankan di dalam setiap partai politik. Di satu sisi di sektor publik kita wajib mendorong meritokrasi dan menolak konflik kepentingan. Maka prinsip yang sama seharusnya juga berlaku bagi partai politik dan kadernya yang terjun ke jabatan publik.
Keuangan partai politik harus semakin transparan, seiring keuangan pemerintah di nasional dan daerah selalu diaudit dan dipantau. Hingga relasi dengan konstituen dibikin lebih akuntabel dengan model distrik yang wilayahnya dipersempit. Sanksi bagi pejabat publik yang melaanggar integritas – menteri, kepala daerah – harus semakin berat dengan demikian rasa keadilan semakin diraih. Dalam hal kedisiplinan, tak hanya soal kader partai harus loyal pada ketua umum, namun juga bagaimana mencegah agar tak mudah lompat pagar. Soal ini sudah jadi pembelajaran politik penting yang meruyak kepercayaan konstituen.
Jika berkaca pada pengalaman terakhir kasus-kasus korupsi yang membuat para politisi tersandera, menunjukkan bahwa sejak Hatta menuliskan pengamatannya pada periode 1950an hingga sekarang, negara ini memang sering melakukan kesalahan sama. Dua hal tadi pastinya bukan hal mudah dan perlu upaya ekstra, mengingat bakal ada resistensi dari partai politik yang kepentingannya tereduksi. Namun, jika ini dianggap sebagai investasi politik, maka hasilnya dapat dipetik pada periode mendatang. Dalam lima tahun ke depan publik juga akan menilai sejauh mana integritas, akuntabilitas, dan kedisiplinan partai politik pendukung dan bagaimana hubungan dengan istana dikelola.